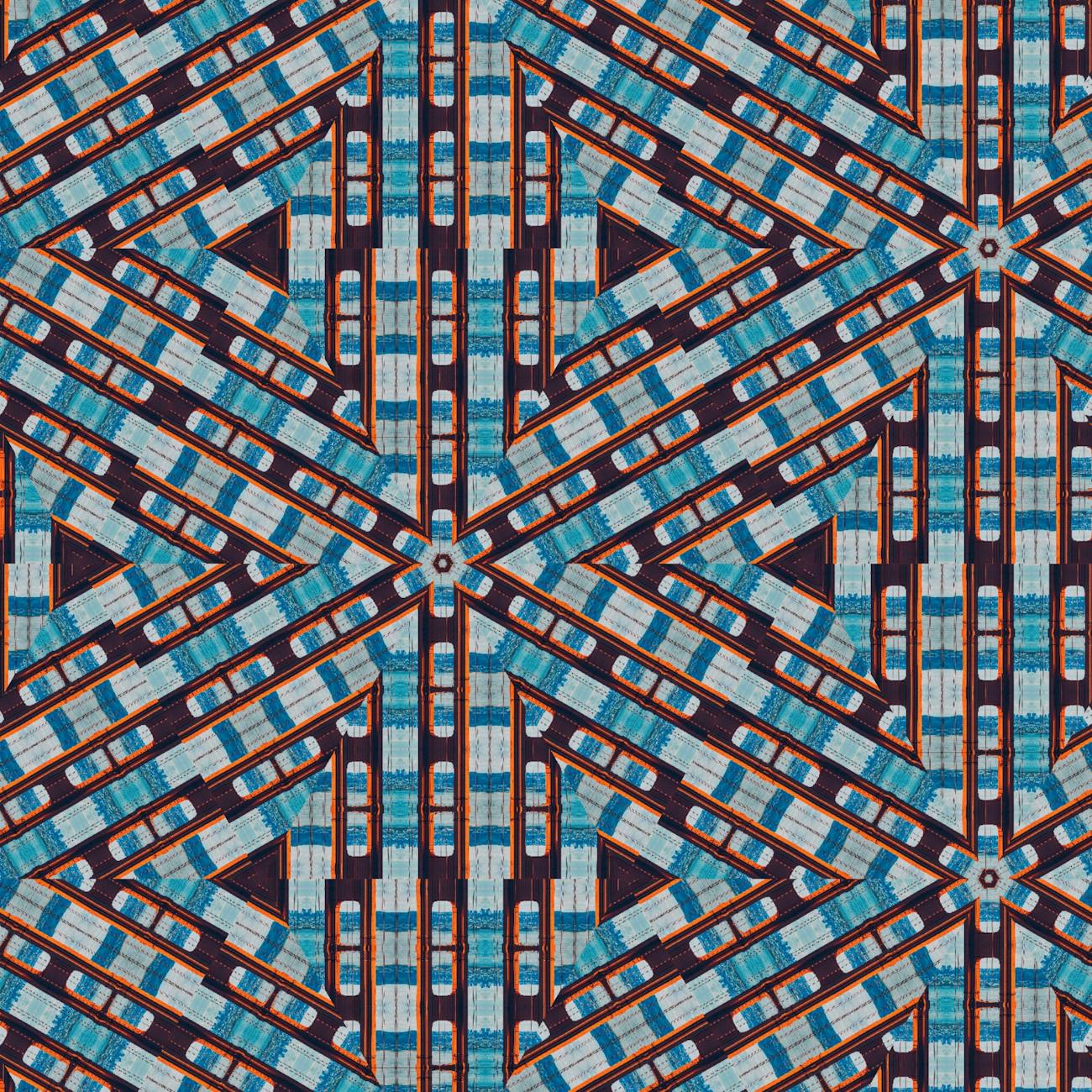
Gedebage, Bandung. Kamis, 29 Januari. Di kawasan ITB Innovation Park, dalam acara Indonesia Semiconductor Summit 2026.
Saya duduk di sana. Mewakili ITS. Menghela napas panjang.
Di depan, paparan dari ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) terpampang di layar raksasa. Angka-angkanya kontras.
Malaysia punya 93 perusahaan semikonduktor. Singapura punya 62. Vietnam punya 39.
Indonesia? Empat. Cuma empat.
Menyakitkan. Di saat tetangga kita sudah berlari kencang memproduksi “otak” bagi peradaban digital, kita masih belajar berjalan. Investasi miliaran dolar mengalir deras ke Penang dan Ho Chi Minh City. Kita di sini, masih berkutat di garis start.
ERIA membuka kartu kita lebih dalam. Mereka menyajikan analisis SWOT yang paradoksal. Tuhan memberkahi tanah ini. Kita kuat di material. Kita punya nikel, pasir silika, timah, hingga logam tanah jarang (Rare Earth). Ini “harta karun” yang dicari seluruh dunia untuk membuat chip.
Tapi, ada ironinya. ERIA memberi catatan merah. Kita lemah di hilirisasi material (refining) dan kepatuhan ESG. Kita punya barangnya, tapi kita tidak bisa mengolahnya menjadi semiconductor-grade materials yang bersih dan sesuai standar global.
Akibatnya? Kita hanya jadi tukang gali. Tetangga yang jadi koki. Kita yang berkeringat, mereka yang menikmati nilai tambahnya.
Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang, membuka acara dengan optimisme. Beliau memamerkan rapor biru manufaktur Indonesia yang tumbuh mengesankan di angka 5,6%. Surplus neraca dagang menembus USD 18 miliar. Mesin ekonomi berpacu, menuju negara industri tangguh.
Namun, di balik data makro itu, terselip fakta pahit. Kita masih defisit parah di sektor elektronik. Apakah kita akan selamanya puas hanya menjadi pasar dan penonton?
Prof. Trio Adiono, guru besar ITB, naik ke panggung.
Ia tidak datang membawa proposal pabrik raksasa (foundry) seharga ratusan triliunan rupiah. Prof. Trio, lewat ICDeC (Indonesia Chip Design Collaborative Center), menawarkan strategi “Gerilya”.
Fokusnya bukan pada pabriknya. Tapi pada desainnya. Pada otaknya. Istilah kerennya. Fabless.
ICDeC merangkul 16 universitas untuk keroyokan. Kami menjahit kekuatan kampus yang punya talenta, dengan industri yang punya pasar. Tujuannya satu, melahirkan desain chip merah putih.
Saya termenung. Teringat sosok Prof. Samaun Samadikun. Bapak Mikroelektronika Indonesia. Puluhan tahun lalu, beliau sudah bermimpi tentang “Bandung High Tech Valley”. Hari ini, di Gedebage, saya melihat mimpi itu mulai mewujud. Kini kita bergerak dalam barisan kolaborasi.
Kenapa momentum ini baru datang sekarang?
Jawabannya ada di buku Chip War karya Chris Miller. Buku ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Miller menceritakan kisah Morris Chang, pendiri TSMC. Dulu, Chang dianggap gila karena ingin membuat pabrik yang hanya menerima pesanan desain orang lain. Intel menertawakannya. Tapi hari ini? TSMC menguasai lebih dari 90% chip tercanggih dunia. Dunia bergantung pada satu perusahaan ini.
Miller menyebut ini sebagai Choke Points atau titik cekik. Siapa yang menguasai leher botol ini, dia menguasai dunia. Bukan lagi nuklir, tapi silikon. AS menahan laju China bukan dengan rudal, tapi dengan memblokir akses ke mesin lithography buatan ASML. Mesin yang presisinya hingga beberapa nanometer.
Mereka butuh sekoci penyelamat. Tempat baru yang netral, stabil, dan punya sumber daya. Istilah geopolitiknya Friend-shoring.
Kementerian Luar Negeri hadir sebagai Co-Host. Pak Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri, naik ke podium bicara soal strategi geopolitik. Ini sinyal, chip bukan lagi sekadar barang dagangan, tapi aset diplomasi.
Indonesia dilirik bukan karena kita paling siap. Tapi karena kita paling strategis. Kita punya silika. Kita punya nikel.
Apakah negara maju rela Indonesia jadi produsen? Terpaksa rela. Karena mereka tidak punya banyak pilihan lain. Ini adalah posisi tawar “Paksa Rela” yang harus kita manfaatkan.
Lantas, bagaimana cara kita masuk gelanggang?
Dirjen Risbang Kemendikti Saintek, Pak Fauzan Adziman, menyajikan peta jalan cerdik, “Design and Off-taker”.
Pemerintah akan “memaksa” pasar domestik menyerap chip lokal. BUMN ditugaskan menjadi pembeli siaga (Anchor Demand). PLN butuh jutaan chip untuk Smart Meter. Pertamina butuh sensor. Himbara butuh smart card.
Pasar ini lumayan, senilai Rp 44 triliun per tahun, kata Pak Fauzan. Strategi ini memberi napas bagi desainer chip lokal untuk hidup.
Tapi, siapa yang membiayai?
Pak Dwi Susanto, Managing Director Danantara memberi angin segar. Danantara membawa konsep “Patient Capital” atau Modal yang Sabar.
Investasi semikonduktor butuh 10 tahun lebih. Danantara siap menanggung risiko di fase awal. Filosofinya realistis. Kata Pak Dwi, Kita tidak perlu mengalahkan negara lain, cukup menjadi bagian tak tergantikan dari mereka.
Strategi ini mengingatkan saya pada hukum fisika zat padat. Energy Band Gap atau Celah Pita Energi. Agar elektron bisa “naik kelas” dari Pita Valensi yang pasif (ibarat kita yang nyaman menjual bahan mentah) menuju Pita Konduksi yang bernilai tinggi, ia butuh suntikan energi masif untuk melompati jurang pemisah (forbidden gap). Hukum alamnya tidak ada lompatan setengah-setengah.
Inilah pertaruhan kita. Investasi Danantara dan diplomasi “Paksa Rela” adalah energi eksitasi itu. Jika energi yang kita himpun ini tanggung, kita tidak akan pernah sampai ke puncak teknologi. Kita justru akan kembali ke dasar sebagai bangsa konsumen, dan seluruh investasi triliunan ini sia-sia.
Semua rencana di atas terdengar indah. Tapi ada satu slide dari Pak Fauzan yang membuat saya tertegun.
Di sana terpampang daftar jabatan spesifik yang wajib kita isi, SoC Architects, Lithography Engineers, hingga Crystal Growth Engineers. Pekerjaan presisi tingkat atom yang menjadi nyawa industri ini.
Talenta ini harusnya diisi dari lulusan Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Fisika, Teknik Material, Teknik Kimia hingga Matematika, Kimia, dan Fisika.
Namun data talentanya menakutkan. Persentase lulusan STEM (Science, Technology, Engineering, Math) kita jauh di bawah bidang lain.
Malaysia bahkan sudah mencetak angka lulusan STEM mendekati 40%. Indonesia? Kita masih berkutat di angka belasan persen.
Siapa yang mau mendesain chip kalau SDM-nya tidak ada? Siapa yang mau kerja di clean room kalau anak mudanya lebih suka jadi pegiat media sosial?
Ini PR besar. Kita harus membuat sains dan teknik menjadi “seksi”.
Apakah masa depan suram? Tidak juga.
Harapan itu muncul dalam wujud seorang wanita muda yang hadir hari itu. Anggi Utami, COO Nicslab.
Nicslab bermain di area deep-tech. Fotonik. Ini bukan lagi listrik, tapi cahaya. Bidang yang saya tekuni di Teknik Fisika. Tahun lalu mereka menang kompetisi global di New York. Anggi membuktikan, anak bangsa bisa bikin instrumen pengendali chip cahaya yang dipakai NASA.
Semikonduktor adalah permainan jangka panjang. Ini maraton, bukan sprint. Kita punya strategi, modal, sejarah visi, dan wadah kolaborasi.
Satu-satunya yang kurang adalah jumlah pasukannya.
Tugas kita adalah mencetak ribuan “Anggi” baru, agar saat fajar industri ini benar-benar terbit, kita tidak bangun kesiangan lagi.
AMH
Agus Muhamad Hatta
Leave a comment